 Adzan Isya belum berkumandang. Wajah Imran terlihat ngantuk,
sekali-kali ia menguap. Adiknya, Marwan duduk bersandar di tiang gubuk.
Ayah dan ibu mereka sudah meninggal setahun yang lalu. Setelah orangtua
mereka meninggal, hidup mereka sebatang kara, sampai akhirnya Haji Ahmad
mempekerjakan mereka sebagai pengembala kambing.
Adzan Isya belum berkumandang. Wajah Imran terlihat ngantuk,
sekali-kali ia menguap. Adiknya, Marwan duduk bersandar di tiang gubuk.
Ayah dan ibu mereka sudah meninggal setahun yang lalu. Setelah orangtua
mereka meninggal, hidup mereka sebatang kara, sampai akhirnya Haji Ahmad
mempekerjakan mereka sebagai pengembala kambing.Imran sudah membungkus dirinya dengan kain sarung, sedang Marwan masih duduk depan gubuk mengawasi kandang kambing.
“Masuklah Wan, sudah malam,” kata Imran dari balik kain sarungnya.
“Belum malam, aku pun belum shalat Isya,” sahut Marwan
Imran tersentak, seakan-akan diingatkan oleh adiknya. Ia langsung bangkit.
“Astagfirullah, aku juga belum shalat.”
Segera Imran turun dari gubuk menuju sumur. Siraman air wudhu terasa menghilangkan rasa ngantuknya. Wajahnya segar kembali.
Marwan juga shalat Isya menjadi makmun di belakang kakaknya. Waktu sesudah shalat bagi mereka adalah saat-saat yang paling menyenangkan. Ada kenikmatan, ketentraman yang merasuk ke dalam hati mereka, ada kebebasan. Mereka serasa telah melunasi utang-utang yang menggunung.
Bintang-bintang malam itu berkedip bersama bulan yang sempurna purnama. Sudah setahun mereka bekerja sebagai pengembala kambing Haji Ahmad. Banyak suka duka yang mereka alami, meskipun dalam kenyataan dukalah yang lebih banyak. Setiap hari sejak fajar terbit hingga mentari terbenam, mereka mengembalakan kambing, menjaga kambing, dan menyabit rerumputan.
Upah mereka satu hari sepuluh ribu rupiah. Makan dua kali sehari, pagi dan malam. Hidup mereka memanglah pahit, namun tidak ada pilihan lain. Ayah tidak punya, Ibu pun telah tiada. Beruntung Haji Ahmad bertemu mereka di mesjid. Haji Ahmad tersentuh hatinya dan iba kepada mereka.
Sebenarnya dulu Imran pernah bersekolah sampai kelas tiga sekolah dasar, sedangkan Marwan hanya sampai kelas dua sekolah dasar. Keadaan telah memaksa mereka putus sekolah. Pekerjaan mereka sekarang adalah mengawasi kambing-kambing supaya tidak masuk kebun orang lain.
Di malam purnama itu, mereka menghitung-hitung penghasilan. Sepuluh ribu rupiah dikali duabelas bulan.
“Mungkin uang kita sudah banyak,” kata Marwan membuyarkan keheningan malam. “Kalau dibelikan kambing betina mungkin sudah beranak banyak”.
“Pelihara kambing harus punya kandang, kau mau simpan dimana?”.
“Mungkin Haji Ahmad mau memberikan sepetak tanah untuk kandang kambing kita”.
“Mana mungkin!” sahut Imran.
“Selama ini kan upah kita simpan pada Haji Ahmad dan belum pernah kita ambil. Bagaimana kalau kita usul kalau upah kita dalam bentuk kambing saja?”
“Benar,” kata Imran. “Saat kita mulai bekerja disini, kambing Haji Ahmad baru enam ekor. Satu jantan dan lima betina. Sekarang kambingnya sudah jadi tiga puluh ekor.”
Mereka berdua saling memandang. Mereka berdua menerawang ke alam khayal.
“Kalau kita membeli kambing betina, pasti akan beranak banyak.” Marwan mulai berkhayal. “Satu ekor betina akan beranak dua. Anaknya nanti beranak lagi. Maka lama-lama kambing kita akan berpuluh-puluh.”
“Saya adalah kakakmu. Bagian kakak harus lebih banyak daripada adik,” kata Imran. “Jika kambingnya ada empat puluh ekor, maka saya dapat duapuluh lima dan bagianmu lima belas ekor.”
“Itu tidak adil namanya,” protes Marwan. “Mestinya saya dapat sembilan belas ekor.”
“Bagianku akan akan kujual semua,” lanjut Imran. “Uang hasil penjualan akan kubelikan tanah dan akan kutanami sayur mayur. Rencanamu bagaimana?”
“Akan kujual sebagian kambingku untuk membeli sepetak tanah di samping kebunmu untuk kujadikan kandang.”
“Kalau begitu kamu harus bikin pagar sebagai batas tanahmu dan tanahku.”
“Aku tidak mau.”
“Kamu harus bikin pagar pembatas!,” kata Imran. “Kamu kan tahu tanahku ditanami sayur mayur. Kambingmu pasti akan merusak tanamanku, dan kamu harus mengganti kerusakannya.”
“Tidak bisa,” kata Marwan. “Kambingku tidak salah, kambing tidak bisa membedakan mana rumput mana tanaman sayur.”
Imran mulai emosi, matanya melotot. “Kambing yang memakan tanaman orang lain jelas bersalah.”
“Kakak yang salah, kenapa tanam sayur di dekat kandang kambingku. Aku tidak akan membayar ganti rugi.”
Tanpa banyak bicara lagi, Imran memukul wajah adiknya. Rasa sakit pukulan Imran di pipi Marwan menyadarkan mereka dari khayalan. Mereka sadar mereka bertengkar karena khayalan. Segalanya masih dalam angan-angan kosong belaka.
“Astagfirullah,” mereka mengucap istigfar dan saling berpandangan.
Cahaya purnama semakin benderang seiring larutnya malam. Mereka diam. Tidak lama kemudian mereka terlelap dalam kelelahan.
Cerpen Karangan: Aksan Lukman
Facebook: Achzan Zanky
Penulis adalah pemuda kalem, pecinta sastra. Menulis adalah penggilan hati dan sebagai ingatan di masa depan…
sumber : http://cerpenmu.com/cerpen-kehidupan/terjebak-khayalan.html







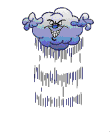


sipp gan
BalasHapushttp://putramodifier.blogspot.com/
HAHA :V
BalasHapus